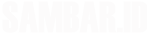Oleh: Arifudin
(Pemuda Pemerhati Pendidikan NTB)
Ada peristiwa yang tak memerlukan banyak kata untuk menjelaskan betapa negara sedang absen. Kematian seorang anak kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, adalah salah satunya. Seorang anak berusia sekitar sepuluh tahun kehilangan nyawa, diduga akibat tekanan batin karena keluarganya tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Penyebabnya begitu sederhana, nyaris tak masuk akal, dan justru karena itu terasa begitu menyakitkan.
Tragedi ini terjadi ketika negara tengah sibuk menghitung dan merayakan besarnya angka anggaran. Dalam APBN 2025, belanja negara melampaui Rp3.000 triliun. Salah satu program yang menonjol adalah Makan Bergizi Gratis, dirancang sebagai kebijakan multi-tahun dengan kebutuhan anggaran ratusan triliun rupiah. Tujuannya baik dan tak layak diperdebatkan: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat. Namun peristiwa di Ngada mengingatkan bahwa kehidupan anak tidak berdiri di atas satu kebutuhan saja.
Pendidikan dasar, yang dijamin konstitusi dan memperoleh alokasi 20 persen dari APBN, seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak-anak dari keluarga miskin. Kenyataannya, sekolah masih menyisakan biaya-biaya kecil yang bagi sebagian orang nyaris tak terasa, tetapi bagi keluarga miskin ekstrem menjadi beban yang menekan dan memalukan. Buku tulis, pena, seragam, dan perlengkapan belajar lainnya tetap harus dicari sendiri. Di titik inilah kata “gratis” kehilangan makna sosialnya.
Masalahnya bukan semata pada keterbatasan anggaran, melainkan pada pilihan politik dalam menyusun prioritas kebijakan. Negara terlihat lebih sibuk membangun program besar yang mudah dipromosikan secara nasional, tetapi abai pada kebutuhan dasar yang sunyi dan tidak spektakuler. Dalam desain kebijakan, keberhasilan sering diukur dari besarnya anggaran dan luasnya cakupan program, bukan dari seberapa jauh ia menjangkau anak-anak yang paling rentan.
Program-program sosial berjalan dalam logika sektoral dan administratif. Program pangan memiliki indikator sendiri, pendidikan memiliki ukuran keberhasilan sendiri, sementara perlindungan sosial bekerja dengan basis data yang kerap tak saling terhubung. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem mudah terlewat di celah antarprogram. Mereka tercatat sebagai penerima di atas kertas, tetapi tetap tertinggal dalam kehidupan nyata. Tragedi di Ngada menunjukkan bahwa ketiadaan integrasi kebijakan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan keselamatan.
Data kemiskinan membantu memahami konteks tragedi ini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa meski angka kemiskinan nasional menurun, wilayah Indonesia Timur termasuk Nusa Tenggara Timur masih berada di atas rata-rata nasional. Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem terus dicanangkan, tetapi di daerah dengan keterbatasan layanan dasar, jarak antara kebijakan dan kenyataan tetap terasa lebar. Anggaran besar tidak selalu berarti kehadiran negara di rumah-rumah paling rapuh.
Yang kerap luput dari perhitungan kebijakan adalah bahwa kemiskinan tidak hanya menggerogoti perut, tetapi juga perasaan. Ia menekan harga diri, menumbuhkan rasa tertinggal, dan perlahan mengikis harapan. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan semacam ini, namun paling jarang didengar suaranya. Mereka tidak memiliki bahasa untuk menjelaskan kecemasan, rasa malu, atau ketakutan akan tertinggal di sekolah. Mereka hanya memendam.
Sekolah, di sisi lain, bekerja dalam keterbatasannya sendiri. Guru dituntut menyelesaikan kurikulum dan beban administrasi, sementara kapasitas untuk membaca tanda-tanda tekanan psikososial murid masih terbatas. Hingga 2025, layanan kesehatan mental anak berbasis sekolah belum terintegrasi kuat, terutama di daerah tertinggal. Tidak semua sekolah memiliki guru konselor atau akses pendampingan profesional. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak yang paling membutuhkan perhatian justru paling mudah luput dari pandangan.
Tragedi di Ngada memperlihatkan betapa biaya tidak langsung pendidikan yang jarang dibicarakan dalam pidato kebijakan memiliki dampak nyata. Kebutuhan sederhana seperti alat tulis masih menjadi kendala serius bagi keluarga miskin ekstrem. Ketika seorang anak merasa tak mampu mengikuti pelajaran karena keterbatasan itu, sekolah tak lagi menjadi ruang aman, melainkan sumber tekanan. Dalam konteks ini, negara gagal membaca bahwa biaya kecil yang diabaikan dalam perencanaan anggaran justru dapat menjadi beban besar bagi anak-anak miskin.
Peristiwa ini tidak seharusnya dibaca sebagai kesalahan individu atau keluarga. Ia adalah cermin kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan berpihak. Jika negara mampu merancang program bernilai ratusan triliun rupiah, maka memastikan ketersediaan alat tulis dan dukungan psikososial bagi siswa miskin seharusnya bukan pekerjaan yang mustahil. Pilihan anggaran selalu mencerminkan keberpihakan, dan dalam kasus ini, keberpihakan itu patut dipertanyakan.
Kematian seorang anak di Ngada adalah peringatan yang tenang, namun keras. Bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada angka dan slogan. Bahwa ukuran keberhasilan negara bukan semata pada besarnya anggaran, melainkan pada kemampuannya memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang merasa hidupnya terlalu berat hanya karena ia lahir miskin.