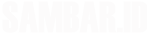Oleh : Arifudin (Mahasiswa S3 Unitomo Surabaya)
Pada tanggal 15 Mei 2025 besok, Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat lumpuh akibat rencana aksi blokade sekelompok masyarakat yang mendesak percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Aksi tersebut, meskipun menyuarakan aspirasi yang telah lama bergulir, justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemaksaan dengan mengorbankan kepentingan umum adalah cara yang tepat untuk memperjuangkan pemekaran wilayah?
Antara Aspirasi dan Anarki
Pemekaran wilayah adalah hak konstitusional masyarakat, selama dilandasi niat tulus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat otonomi daerah. Dalam konteks Pulau Sumbawa, gagasan untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan membentuk provinsi sendiri telah lama menjadi wacana. Alasan yang dikemukakan pun terdengar masuk akal: ketimpangan pembangunan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, keterbatasan akses birokrasi, serta kebutuhan akan percepatan pembangunan infrastruktur.
Namun, sahnya sebuah aspirasi tidak otomatis melegitimasi segala bentuk aksi yang digunakan untuk menyuarakannya. Ketika pelabuhan, yang merupakan jalur utama logistik, ekonomi, dan pergerakan orang, dijadikan sasaran blokade, maka yang dikorbankan bukan hanya pemerintah, tapi rakyat itu sendiri. Petani, pedagang kecil, wisatawan, hingga pelajar ikut terdampak. Solidaritas terhadap pemekaran bisa berubah menjadi antipati jika dampaknya justru menyengsarakan publik.
Pemekaran: Solusi atau Ilusi?
Pemekaran wilayah seringkali ditawarkan sebagai solusi instan terhadap ketimpangan pembangunan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa banyak daerah otonomi baru (DOB) justru kesulitan menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Studi Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa sebagian besar DOB tidak mampu mandiri secara fiskal dan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat.
Lebih jauh lagi, pemekaran sering kali ditunggangi kepentingan elit lokal. Provinsi baru berarti jabatan baru: gubernur, wakil gubernur, kepala dinas, DPRD, dan jajaran birokrasi lainnya. Celakanya, kepentingan ini tidak selalu berjalan seiring dengan kepentingan rakyat. Akibatnya, alih-alih membawa kesejahteraan, pemekaran justru melahirkan pemborosan anggaran, birokrasi baru yang tidak efisien, dan konflik antarwilayah atau antaraktor politik lokal.
Partisipasi dan Rasionalitas
Aspirasi pemekaran seharusnya dibangun di atas data dan kajian yang objektif, bukan emosi atau tekanan. Kesiapan administratif, ketersediaan sumber daya manusia, potensi ekonomi, dan keberlanjutan fiskal adalah beberapa prasyarat penting. Prosesnya pun harus partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat: tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, kaum muda, dan kelompok rentan. Dengan begitu, pemekaran menjadi kesepakatan bersama, bukan sekadar proyek politik segelintir orang.
Pemerintah pusat juga tidak bisa lepas tangan. Penundaan terhadap usulan PPS selama bertahun-tahun tanpa komunikasi yang jelas hanya menambah ketidakpuasan. Pemerintah perlu bersikap terbuka, transparan, dan komunikatif, menjelaskan tahapan serta kendala yang dihadapi. Jika memang belum memenuhi syarat, sampaikan dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Jalan Tengah yang Bijak
Blokade Poto Tano seharusnya menjadi alarm, bukan justifikasi. Ia menunjukkan ada kegelisahan dan aspirasi yang belum terjawab. Namun, menjadikan rakyat sebagai korban tekanan politik adalah langkah yang keliru. Perjuangan politik, terlebih untuk sesuatu sebesar pembentukan provinsi baru, memerlukan keteladanan, konsistensi, dan etika.
Aspirasi pemekaran akan lebih bermakna jika dikawal dengan narasi yang cerdas, strategi yang elegan, dan dukungan yang luas dari akar rumput. Sebaliknya, jika perjuangan ini berubah menjadi aksi koersif yang melumpuhkan ruang publik, maka tujuan mulia itu bisa kehilangan makna dan bahkan dukungan.