OPINI - Riuh rendah Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) Universitas Mataram yang baru saja usai tak ubahnya sebuah mikrokosmos.
Ia bukan sekadar pesta demokrasi di lingkar kampus yang semestinya steril dari intrik murahan, melainkan menjelma etalase telanjang, barangkali cermin buram, dari praktik politik yang lebih besar.
Di panggung utama, jargon "kepentingan rakyat" dan "demokrasi sejati" lantang dikumandangkan.
Namun, di balik tirai beludru yang coba menutupi, tercium aroma tak sedap dari manuver-manuver yang sarat kepentingan pragmatis, menyeret bayang-bayang Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke dalam pusaran.
Lakon di Unram ini bisa jadi adalah babak penting untuk menguji: apakah Korpus BEM SI, dengan segala klaim heroiknya, benar-benar pelindung moral, ataukah sekadar kumpulan aktor yang piawai memainkan peran ganda?
Narasi yang bergulir jika dicermati, penuh ironi.
Tiga pasang calon bersiap merebut kursi tertinggi mahasiswa Unram. Satu kubu—yang kelak menjadi episentrum kontroversi dan akhirnya tersisih—sejak awal sudah "diberi hati".
Keterlambatan pendaftaran mereka, yang semestinya menggugurkan, akhirnya dimaafkan atas nama "marwah demokrasi dan proses pembelajaran".
Sebuah kelonggaran yang patut dicatat. Namun, kemurahan hati panitia tak berbalas kepatuhan. Puncaknya, pada proses verifikasi berkas, kubu ini kembali terjerat masalah: dokumen-dokumen mereka dinyatakan "banyak cacatnya", bahkan terendus dugaan plagiasi sertifikat Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM).
Sebuah pelanggaran etika dan administratif yang tak bisa dianggap sepele dalam kontestasi yang mengedepankan integritas.
Akibatnya, hanya pasangan Nazir-Yoga yang dinyatakan lolos dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Sontak, kubu yang gugur tak terima.
Protes dilayangkan, kritik tajam dialirkan. Tak cukup di situ, birokrasi kampus pun "ditarik-tarik" untuk turun tangan, dengan tuntutan pemilihan ulang.
Dalihnya? Sungguh mulia terdengar di permukaan: "misi penyelamatan demokrasi" dibalik itu semua kuat dugaan bahwa ini salah satu proses untuk mengamankan gerbong nasional.
Frasa ini, "gerbong nasional", adalah kata kunci yang membuka pintu ke panggung yang lebih besar, panggung di mana BEM SI memainkan peran sentral.
Di sinilah teori dramaturgi Erving Goffman menemukan panggungnya yang paling relevan.
Goffman mengajarkan kita tentang "panggung depan" (front stage), tempat para aktor menampilkan citra ideal sesuai harapan audiens, dan "panggung belakang" (back stage), ruang privat tempat para aktor bisa melepaskan topeng, beristirahat, dan mempersiapkan siasat untuk penampilan berikutnya.
Panggung depan BEM SI, terlebih dengan status BEM Unram periode sebelumnya sebagai Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia "Rakyat Bangkit", adalah citra agung sebagai pembela kaum lemah, garda terdepan kritik terhadap kebijakan zalim, dan penjaga moral bangsa.
Narasi "demokrasi", "keadilan", dan "keberpihakan pada rakyat" menjadi naskah utama yang dilafalkan dengan fasih. Kubu yang merasa terzalimi di Pemira Unram pun tampaknya meminjam naskah serupa, berteriak tentang demokrasi yang dikhianati, seolah mereka adalah korban tunggal dari sebuah sistem yang korup.
Namun, apa yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang, menurut kepingan-kepingan cerita yang berhasil menyelinap keluar dari Mataram? Alih-alih menjaga marwah demokrasi dengan integritas dokumen—sebuah ironi mengingat kelonggaran yang telah mereka nikmati—kubu yang begitu vokal ini justru terbelit dugaan plagiasi.
Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi potensi kesengajaan untuk memanipulasi syarat demi meraih kekuasaan.
Inikah potret "pembelajaran demokrasi" yang dimaksud? Prospek "cawe-cawe" Ketua BEM Unram sebelumnya, yang notabene memegang kendali Korpus BEM SI "Rakyat Bangkit", demi "mengamankan gerbongnya" di Unram, melukiskan betapa vitalnya posisi ketua BEM lokal bagi konstelasi nasional.
Kekhawatiran bahwa "gerbong nasional mereka pun bubar" jika Unram lepas dari genggaman mereka, menunjukkan adanya taruhan yang jauh lebih besar dari sekadar Pemira tingkat Universitas.
Ini adalah tentang mempertahankan hegemoni, jalur komando, dan mungkin, akses terhadap sumber daya atau pengaruh di tingkat nasional.
Intervensi ini semakin keruh dengan dugaan keterlibatan Rektorat Unram, yang kebetulan juga berada dalam tahun politik pemilihan Rektor. Isu "deal-dealan" untuk "mengamankan suara kementerian"—difasilitasi oleh senior kubu kalah yang kini menduduki kursi menteri—menjadi bumbu penyedap yang membuat lakon ini semakin mirip opera sabun politik ketimbang ajang adu gagasan mahasiswa.
Di sini, kepentingan personal dan institusional berkelindan, menjadikan Pemira sebagai medan pertaruhan sampingan.
Pada panggung belakang inilah, karakter "licik"—dalam arti siasat yang tak mengindahkan etika demi tujuan pragmatis—menemukan manifestasinya.
Di depan publik, mereka adalah ksatria berbaju zirah kebenaran. Namun di belakang layar, mereka diduga menjadi pemain catur yang tak segan mengorbankan bidak demi menyelamatkan raja atau ratu. "Kepentingan rakyat" dan "demokrasi" yang mereka teriakkan di panggung depan, di panggung belakang bisa jadi hanya menjadi kostum yang dikenakan untuk memukau audiens, menutupi agenda sesungguhnya: pelestarian kekuasaan faksional di dalam tubuh BEM SI.
Jika benar demikian, Korpus BEM SI sebagai entitas yang kerap memposisikan diri sebagai penjaga moral dan penyambung lidah rakyat, perlu melakukan introspeksi mendalam.
Bagaimana mungkin mereka bisa lantang mengkritik praktik-praktik kotor di level negara, jika di "rumah" mereka sendiri, dalam proses regenerasi kepemimpinan di tingkat paling dasar.
Diduga terjadi praktik-praktik yang justru mengkhianati nilai-nilai yang mereka perjuangkan? Apakah "Rakyat Bangkit" hanya menjadi slogan kosong ketika proses kaderisasinya diwarnai oleh dugaan plagiasi, lobi-lobi transaksional, dan intervensi demi kepentingan segelintir elite?
Publik mahasiswa, dan masyarakat yang lebih luas, berhak untuk skeptis. Siapa sesungguhnya yang dilayani ketika topeng "pembela rakyat" begitu gagah dikenakan
Sementara di belakang layar, skenario "licik" demi kepentingan pragmatis segelintir elite dimainkan dengan begitu rapi?
Ironisnya, mereka yang dituduh "merusak tatanan demokrasi" dengan tidak melengkapi berkas dan berniat plagiasi, justru adalah pihak yang paling nyaring berteriak tentang kecurangan.
Ini adalah pertunjukan memukau tentang bagaimana korban bisa sekaligus menjadi pelaku, tergantung dari sudut mana panggung itu dilihat.
Pemira Unram mungkin hanya satu episode kecil dalam epos panjang gerakan mahasiswa Indonesia.
Tetapi, ia mengirimkan sinyal yang memekakkan telinga tentang bahaya laten pragmatisme, politisasi yang kebablasan, dan kerapuhan idealisme di jantung gerakan mahasiswa.
Ketika panggung belakang tak lagi bisa disembunyikan, dan aroma siasat licik menguar lebih kuat daripada parfum idealisme, kepercayaan adalah taruhan terbesarnya.
Jangan sampai, gerakan mahasiswa yang kita banggakan, justru menjadi sekolah pertama bagi lahirnya politisi-politisi transaksional yang lihai bersandiwara, mengorbankan substansi demi ilusi panggung depan yang memukau.
Karena pada akhirnya, rakyat yang namanya selalu dibawa-bawa itu, hanya akan menjadi penonton yang lagi-lagi dikecewakan. (*)
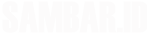

.png)






