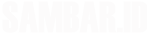Oleh: Arifudin
Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Lombok Barat, NTB dan Kader PDI Perjuangan
Setiap negara punya simbol, setiap bangsa punya teladan, dan setiap generasi membutuhkan figur moral yang menjadi kompas perjuangan. Gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar selempang kehormatan, bukan pula medali pelengkap album sejarah. Gelar itu adalah deklarasi nilai: siapa yang layak menjadi wajah moral bangsa, siapa yang pantas dijadikan rumah teladan generasi, dan siapa yang kisah hidupnya layak dikenang sebagai arah perjalanan masa depan. Karena itu, wacana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar perdebatan administratif, melainkan perdebatan tentang hati nurani kolektif bangsa.
Ketika Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa pahlawan adalah simbol negara yang lahir dari keberpihakan pada kemanusiaan, pembelaan kepada rakyat, dan keteladanan untuk masa depan, saya melihat itu bukan hanya pernyataan politik. Itu adalah parameter etika berbangsa. Bu Mega menegaskan, pahlawan harus hadir sebagai pelopor dari suara rakyat, bukan figur yang kisahnya ditulis ulang oleh nostalgia kekuasaan. Ia harus menjadi contoh ideal bagi anak bangsa, bukan figur yang meninggalkan luka yang belum disembuhkan.
Dengan standar itu, mari kita letakkan sejarah secara jujur di atas meja. Soeharto adalah bagian dari perjalanan Indonesia itu tak terbantahkan. Namun, bagian dari sejarah tidak otomatis berarti layak menjadi teladan bangsa. Ada perbedaan mendasar antara mengakui sejarah dan mengagungkan sejarah. Ada jurang besar antara mencatat peristiwa dan memberi legitimasi moral.
Selama 32 tahun Orde Baru, Indonesia memang menyaksikan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Tetapi pertanyaannya bukan hanya apa yang dibangun, melainkan bagaimana cara membangunnya. Stabilitas dibangun bukan di atas konsensus, tetapi di atas pembungkaman. Pertumbuhan terjadi bukan melalui kompetisi sehat, melainkan melalui kedekatan dengan kekuasaan. Jalan, gedung, dan jembatan yang berdiri hari ini tidak bisa dipisahkan dari cerita lain di belakangnya: kebebasan yang disekat, kritik yang dibungkam, pers yang dibredel, dan oposisi yang dicap anti-negara.
Lebih jauh dari itu, sejarah kita mencatat luka-luka besar yang tidak pernah benar-benar sembuh. Tragedi 1965 dengan ratusan ribu nyawa melayang tanpa proses hukum. Operasi Petrus yang mengubur keadilan di temaram malam. Peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari yang berdarah. Aktivis 1998 yang hilang tanpa jejak, menyisakan ruang kosong di meja makan keluarga mereka hingga hari ini. Ini bukan catatan kaki sejarah, ini adalah bab gelap yang seharusnya menjadi alasan bangsa untuk berhenti sejenak, bukan menabuh genderang perayaan.
Pahlawan sejati membebaskan rakyatnya, bukan membuat rakyat takut pada negaranya sendiri. Pahlawan menumbuhkan keberanian berpikir, bukan menormalisasi budaya “asal bapak senang”. Pahlawan mengangkat martabat manusia, bukan menundukkan mereka demi stabilitas semu. Dan yang terpenting, pahlawan tidak meninggalkan luka yang harus diwarisi lintas generasi.
Sebagai kader PDI Perjuangan, saya meyakini garis perjuangan yang diajarkan Bung Karno dan Bu Mega: politik harus memanusiakan manusia, kekuasaan harus memuliakan rakyat, dan negara harus hadir sebagai pelindung, bukan ancaman. Ketika prinsip ini kita benturkan dengan realitas Orde Baru, kita harus jujur mengakui bahwa ada jurang nilai yang sulit diseberangi dengan alasan apa pun.
Sebagai Ketua Banteng Muda Indonesia Lombok Barat, saya juga berbicara sebagai representasi generasi muda. Generasi kami menghormati sejarah, tetapi tidak ingin dibelenggu nostalgia. Kami ingin menatap masa depan dengan keberanian, bukan dengan romantisasi masa ketika kritik dibungkam dan demokrasi diseragamkan. Kami butuh teladan keberpihakan, bukan teladan keberlangsungan kekuasaan. Kami ingin sosok pahlawan yang mengajarkan kami arti merdeka yang sesungguhnya: berani bersuara, berani membela rakyat, berani melawan ketidakadilan.
Gelar pahlawan adalah investasi karakter bangsa di masa depan. Ia bukan alat rehabilitasi figur masa lalu, bukan dekorasi kekuasaan, bukan juga tiket untuk memutihkan sejarah yang penuh luka. Jika kita salah memilih teladan, kita sedang mengajari generasi selanjutnya bahwa kekuasaan yang lama, pembangunan yang timpang, dan represi yang sistemik bisa dimaafkan selama dikemas dengan narasi kejayaan. Itu pesan yang berbahaya bagi jiwa demokrasi, kemanusiaan, dan masa depan Republik.
Karena itu saya menegaskan dengan terang, tanpa kebencian tetapi dengan kejernihan:
Soeharto adalah bagian dari sejarah Indonesia, tetapi bukan sosok yang layak menjadi kompas moral bangsa.
Bangsa ini tidak boleh memuliakan luka sebagai teladan.
Pahlawan harus memerdekakan rakyatnya, bukan merapikan kekuasaan di atas penderitaan mereka.
Masa depan Indonesia berhak atas pahlawan yang memberi terang, bukan bayang-bayang. Karena sejatinya, pahlawan bukan yang paling lama berkuasa, melainkan yang paling jujur membela rakyatnya. (*)