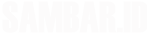Oleh: Hadian Supriatna
Bandung,SAMBAR ID//Desa adalah fondasi paling dasar dari kedaulatan bangsa. Di sanalah rakyat berdaulat secara nyata: merencanakan pembangunan, mengelola potensi lokal, dan menentukan arah kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warganya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, arah perjalanan desa perlahan bergeser. Kemandirian yang dulu menjadi cita-cita Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 kini mulai memudar. Desa seolah kehilangan arah dan daya untuk menegakkan hak atas pemerintahannya sendiri.
Republik Desa kini tak lagi berdaulat. Haluan dan cara pandang baru ber desa musnah sudah.”
Kalimat ini bukan sekadar keluhan emosional, tetapi jeritan nurani dari para pemerhati desa yang melihat bagaimana semangat otonomi desa semakin dikungkung oleh kebijakan yang seragam dari atas
Desa yang Terkungkung oleh Program Nasional
Banyak kebijakan baru lahir dengan dalih percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan integrasi program nasional. Namun, dalam praktiknya, desa sering kali hanya menjadi pelaksana, bukan perencana. Pemerintah pusat menginstruksikan berbagai program dengan desain tunggal, sementara kepala desa dan perangkatnya dipaksa menyesuaikan tanpa ruang untuk menimbang kebutuhan riil di lapangan.
Prof. Sutoro Eko, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, menegaskan bahwa “desa bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan pemerintahan lokal yang memiliki hak asal-usul dan kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri.” Ketika kebijakan nasional terlalu sentralistik, desa kehilangan fungsi demokratisnya.
Dr. Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN, juga mengingatkan bahwa “birokratisasi berlebihan justru menumpulkan inovasi desa.” Desa tidak akan berkembang jika setiap langkahnya harus menunggu instruksi dari atas.
Kemandirian yang dijanjikan Undang-Undang Desa perlahan terkikis. Dana desa yang seharusnya menjadi motor pembangunan lokal kini justru menjadi alat untuk membiayai proyek-proyek nasional yang belum tentu sejalan dengan prioritas masyarakat desa. Kepala desa dan aparatnya pun berada dalam posisi dilematis: antara melayani rakyatnya atau sekadar melaksanakan perintah birokrasi.
Musnahnya Cara Pandang Ber desa
“Cara pandang berdesa” yang dulu dibangun atas semangat gotong royong, kearifan lokal, dan partisipasi warga kini mulai pudar. Konsep pembangunan desa berkeadilan sosial digantikan oleh pola administratif yang serba laporan, target, dan seremonial.
Desa kini bukan lagi ruang hidup masyarakat yang tumbuh dari budaya lokal, melainkan sekadar titik koordinat di peta kebijakan nasional.
Prof. Yayan Sopyan, sosiolog pedesaan dari Universitas Padjadjaran, menyebut fenomena ini sebagai “krisis makna berdesa.” Menurutnya, “desa kini sibuk mengerjakan administrasi, bukan lagi menghidupkan solidaritas sosial.”
Padahal, nilai-nilai luhur desa Indonesia – seperti musyawarah mufakat, kebersamaan, dan pengelolaan sumber daya lokal – telah terbukti menjadi benteng sosial yang kuat sejak masa sebelum republik ini lahir. Ketika haluan pembangunan desa bergeser dari rakyat ke birokrasi, maka yang hilang bukan sekadar wewenang administratif, tetapi juga jati diri dan martabat desa itu sendiri.
Dr. Budiman Sudjatmiko, inisiator gerakan Desa Maju, pernah menegaskan bahwa “desa yang kuat adalah desa yang berdaulat secara ekonomi dan sosial, bukan hanya administratif.” Sayangnya, arah kebijakan saat ini justru mengikis keberanian desa untuk berkreasi dan berdiri di atas kaki sendiri.
Membangun Kembali Daulat Desa
Kedaulatan desa bukan berarti memisahkan diri dari negara, melainkan menegaskan bahwa desa adalah subjek pembangunan, bukan objek kebijakan. Negara seharusnya hadir untuk memperkuat, bukan mengatur secara berlebihan.
Dibutuhkan cara pandang baru berdesa yang menempatkan kepala desa dan masyarakatnya sebagai mitra strategis, bukan bawahan dalam sistem birokrasi.
Prof. Bambang Purwoko, ahli tata kelola desa UGM, berpendapat bahwa “negara perlu berani menata ulang relasi kekuasaan dengan desa. Desa harus diposisikan sebagai arena demokrasi lokal yang nyata, bukan sekadar pelaksana APBN.”
Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan partisipasi dalam setiap kebijakan yang menyentuh desa. Desa harus kembali diberi ruang untuk berinovasi, menumbuhkan ekonomi lokal, serta mengelola potensi wilayahnya sesuai kearifan yang hidup di dalamnya.
Kedaulatan desa juga berarti keberanian untuk menolak kebijakan yang mengabaikan prinsip keadilan sosial. Desa harus berani menyuarakan kepentingan rakyatnya agar tidak terseret arus politik anggaran semata.
Saatnya Menata Ulang Haluan
Jika arah pembangunan nasional terus menempatkan desa sebagai pelaksana tanpa kedaulatan, maka cita-cita besar membangun Indonesia dari pinggiran hanya akan menjadi slogan. ketika menyebut bahwa haluan dan cara pandang baru berdesa telah musnah. Namun, dari kesadaran inilah semangat baru bisa lahir.
Dr. Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), menegaskan bahwa “tanpa desentralisasi sejati hingga ke level desa, maka otonomi daerah hanya akan berhenti di kabupaten dan kota.”
Artinya, revitalisasi desa menjadi prasyarat utama agar demokrasi lokal benar-benar hidup.
Sudah saatnya desa kembali berdiri tegak sebagai republik kecil dalam republik besar, berdaulat atas tanahnya, rakyatnya, dan masa depannya sendiri. Karena tanpa desa yang berdaulat, mustahil Indonesia bisa benar-benar merdeka dalam arti yang sesungguhnya.(Red)
"Arie Gusti S"