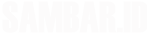Oleh : Safran J. Umar (Sekretaris LS-ADI Komisariat Universitas Alkhairaat)
SAMBAR.ID, Opini, Palu, Sulteng - Pada 2 Januari Indonesia resmi memasuki babak baru dalam sejarah hukum pidana dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Penggantian KUHP warisan kolonial Belanda kerap dipandang sebagai langkah progresif untuk menegaskan kedaulatan hukum nasional.
Namun, di balik semangat pembaruan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah KUHP baru benar-benar mencerminkan kemajuan hukum, atau justru menghadirkan ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dalam negara demokratis?
Pertanyaan ini perlu untuk disuarakan, khususnya oleh organisasi masyarakat sipil seperti Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), yang menaruh perhatian pada isu sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Dari sisi historis dan simbolik, lahirnya KUHP baru patut diapresiasi. Selama puluhan tahun, Indonesia hidup dengan sistem hukum pidana yang dirancang untuk kepentingan kolonial, bukan untuk masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
KUHP baru berupaya menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, budaya lokal, serta dinamika sosial Indonesia modern. Dalam konteks ini, pembaruan KUHP dapat dibaca sebagai upaya dekolonisasi hukum dan penguatan identitas nasional.
Namun, kemajuan hukum tidak semata diukur dari siapa yang menyusunnya, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Di titik inilah kritik terhadap KUHP baru menguat.
Sejumlah pasal menuai kontroversi karena dinilai berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, terutama pasal-pasal terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, lembaga negara, serta pengaturan ranah privat warga negara.
Pasal 218 KUHP baru tentang penghinaan terhadap martabat presiden, misalnya, menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya “pasal karet” yang lentur dalam penafsirannya. Dalam praktik, kritik yang seharusnya menjadi bagian sehat dari demokrasi berisiko disamakan dengan penghinaan.
Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan dan dimaksudkan untuk melindungi kehormatan, bukan membungkam kritik, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa norma hukum yang rumusannya samar kerap disalahgunakan untuk menekan suara oposisi dan masyarakat sipil.
Selain itu, pengaturan mengenai ranah privat juga memicu perdebatan serius. Negara dinilai terlalu jauh masuk ke wilayah personal warga negara yang seharusnya dilindungi dari intervensi hukum pidana.
Jika hukum pidana digunakan untuk mengatur moralitas secara berlebihan, maka risiko kriminalisasi terhadap perilaku privat yang tidak merugikan orang lain menjadi nyata. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum modern yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama, sepanjang tidak melanggar hak orang lain.
Pada titik ini, KUHP baru berada di persimpangan antara ketertiban dan kebebasan. Negara memang memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas, kehormatan institusi, dan nilai sosial.
Namun, kepentingan tersebut tidak boleh mengorbankan hak-hak fundamental warga negara untuk berpendapat, mengkritik, dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Demokrasi tidak hanya diukur dari penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana negara menjamin ruang aman bagi warganya untuk berbicara.
Atas dasar itu, Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menyatakan penolakan tegas terhadap sejumlah ketentuan dalam KUHP baru yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia.
Pembaruan hukum pidana seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan, bukan sebaliknya, justru membuka ruang baru bagi kriminalisasi dan pembungkaman suara kritis masyarakat.
Tanpa pengawasan publik yang kuat dan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi, KUHP baru berisiko menjadi ancaman senyap bagi kebebasan sipil di Indonesia.***