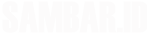Oleh: Arifudin
Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Dan Literasi DPD KNPI NTB
Keputusan pemerintah mengalokasikan hampir sepertiga anggaran pendidikan nasional tahun 2026 untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan penilaian jernih dan berbasis data. Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun, sekitar Rp335 triliun dialokasikan ke Badan Gizi Nasional untuk menjalankan MBG, dengan sekitar 67 persen dananya diambil dari pos pendidikan. Artinya, lebih dari Rp220 triliun dana pendidikan bergeser ke program makan. Dari sudut pandang pemerhati pendidikan, kebijakan ini perlu dipertanyakan dari sisi prioritas dan dampaknya terhadap mutu pembelajaran jangka panjang.
Tidak ada perdebatan bahwa gizi yang baik mendukung kesiapan belajar siswa. Di banyak daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat, masih ditemukan murid datang ke sekolah tanpa asupan memadai. Intervensi gizi bisa menjadi bagian dari solusi sosial. Namun pendidikan berkualitas tidak pernah berdiri hanya di atas piring makan. Ia bertumpu pada kualitas guru, kepastian proses belajar, dan ekosistem sekolah yang sehat. Ketika fondasi ini rapuh, program pendukung sebesar apa pun tidak akan menghasilkan dampak optimal.
Masalah paling mendesak pendidikan kita hari ini justru terletak pada kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Data Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menunjukkan terdapat sedikitnya 700.000 guru honorer di Indonesia. Survei IDEAS dan GREAT Edunesia 2025 mencatat 74 persen guru honorer masih bergaji di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan sebagian di bawah Rp500 ribu. Fakta di lapangan menunjukkan ada guru PPPK di daerah tertentu menerima sekitar Rp139 ribu, dan ada guru honorer yang setelah puluhan tahun mengabdi justru mengalami pemotongan hingga sekitar Rp223 ribu per bulan. Ini bukan sekadar angka ini potret rapuhnya penghargaan terhadap profesi pendidik.
IDEAS dalam policy brief Januari 2026 juga menghitung bahwa dana sekitar Rp156,6 triliun cukup untuk membiayai pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia, memberi beasiswa hampir 3 juta mahasiswa miskin, sekaligus menaikkan gaji 2,1 juta guru honorer setara upah minimum provinsi. Perbandingan ini menunjukkan adanya pilihan kebijakan yang nyata: apakah anggaran pendidikan difokuskan terlebih dahulu ke kualitas pembelajaran, atau diperluas ke program kesejahteraan pendukung.
Pendukung MBG menekankan dampak gizi terhadap konsentrasi belajar, dan itu benar. Namun riset pendidikan selama puluhan tahun konsisten menunjukkan bahwa faktor guru adalah variabel paling menentukan dalam peningkatan hasil belajar. Intervensi gizi membantu, tetapi tidak menggantikan kualitas pengajaran. Karena itu, dalam hirarki belanja pendidikan, penguatan kualitas dan kesejahteraan guru semestinya menjadi prioritas utama.
Kesiapan implementasi MBG juga perlu dicermati. Sejak diluncurkan awal tahun ini, tercatat lebih dari 4.000 siswa mengalami keracunan makanan. Pemerintah menyatakan tingkat insiden hanya sekitar 0,0087 persen dan menyebut tingkat keberhasilan hampir sempurna. Namun dalam standar layanan publik, ribuan kasus keracunan pada program untuk anak sekolah tetap merupakan sinyal serius tentang pengawasan mutu, higienitas dapur, dan kontrol distribusi pangan. Program dengan target 82,9 juta penerima dan pembangunan 33.000 dapur dalam satu tahun jelas membutuhkan kapasitas pengawasan luar biasa besar.
Dimensi rasa keadilan juga tidak bisa diabaikan. Saat sekitar 32.000 pegawai inti dapur MBG diproyeksikan diangkat menjadi PPPK, banyak guru honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun masih menunggu kepastian status. Dalam komunitas pendidikan, rasa keadilan kebijakan sangat memengaruhi moral dan motivasi kolektif. Ketimpangan simbolik seperti ini berisiko menurunkan kepercayaan terhadap arah kebijakan pendidikan.
Dari sisi tata anggaran, memasukkan MBG ke dalam pos pendidikan juga memunculkan perdebatan. Konstitusi mensyaratkan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Saat ini tercatat 20,01 persen, tetapi sudah termasuk MBG. Tanpa MBG, porsinya diperkirakan hanya sekitar 14,2 persen. Secara fungsi, program makan lebih dekat dengan sektor kesehatan dan perlindungan sosial, meskipun dilaksanakan di sekolah. Ketepatan klasifikasi penting agar makna investasi pendidikan tidak bergeser.
Solusinya bukan memilih antara gizi siswa atau kesejahteraan guru. Keduanya penting. Namun urutan prioritas dan sumber pembiayaan harus seimbang. Program makan dapat difokuskan terlebih dahulu pada wilayah rawan gizi dengan skema lintas sektor. Sementara itu, reformasi kesejahteraan guru honorer harus dipercepat sebagai agenda inti pendidikan nasional. Jika tujuan kita mencerdaskan bangsa, maka memperkuat guru adalah titik mulai yang tidak boleh dikalahkan oleh program yang bersifat pendukung.