Oleh: Muhammad Radun
SAMBAR.ID, Opini - Dalam sebuah negara hukum, keadilan seharusnya menjadi hak dasar yang bisa diakses oleh siapa pun tanpa memandang status sosial maupun isi dompet.
Namun, realita di lapangan seringkali menyisakan tanda tanya besar: Apakah keadilan memang terlalu sulit untuk ditegakkan secara murni?
Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Belakangan, publik disuguhi fenomena memprihatinkan di mana hukum seolah-olah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.
Muncul narasi-narasi pahit di tengah masyarakat bahwa untuk mendapatkan haknya, seseorang harus "menebus" keadilan tersebut dengan sejumlah uang. Jika ini benar, maka hukum bukan lagi menjadi panglima, melainkan alat bagi mereka yang memiliki kuasa finansial.
Lebih jauh lagi, kita perlu merefleksikan kembali fungsi hukum itu sendiri. Apakah hukum saat ini masih berdiri teguh sebagai instrumen pencari kebenaran, atau justru telah bergeser menjadi alat kriminalisasi untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu yang tidak disukai?
Sebagai bukti dari keresahan ini, sebuah laporan hukum telah dilayangkan dan penetapan tersangka telah dilakukan Namun, di balik proses formal tersebut, beredar isu yang sangat mencederai rasa keadilan: dugaan adanya "tarif" tertentu—sebut saja angka 15 juta rupiah—yang konon bisa menjamin posisi seseorang tetap aman di mata hukum.
Kondisi ini memperkuat stigma negatif "No Viral, No Justice". Seolah-olah, tanpa adanya sorotan kamera dan tekanan publik di media sosial, keadilan akan tetap tertidur pulas. Rakyat kecil dipaksa berteriak di ruang digital hanya untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka sejak awal.
Melalui tulisan ini, saya mengajak teman-teman dan pembaca sekalian untuk memberikan saran dan pandangan di kolom komentar. Mari kita kawal proses ini bersama. Karena jika diam adalah emas, maka dalam urusan ketidakadilan, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran.***
"Semoga keadilan masih berpihak pada mereka yang benar".
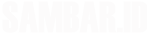





.jpg)





