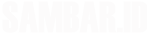Sambar.id Boyolali - Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, ketika Disdukcapil Kabupaten Boyolali menolak pelayanan dengan alasan dokumen dasar tidak lengkap tanpa menawarkan solusi, persoalan ini tidak lagi bersifat teknis, melainkan menyentuh jantung keadilan dan kehadiran negara.
Negara hukum tidak boleh berhenti pada prosedur. Ia wajib menghadirkan keadilan substantif.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, serta memberikan kepastian hukum. Pasal 4 UU tersebut secara eksplisit menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar kepatuhan administratif.
Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin pencatatan peristiwa penting warga negara. Dalam praktiknya, regulasi turunan seperti Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 justru membuka ruang penggunaan kesaksian, fakta sosial, dan mekanisme penetapan pengadilan dalam kondisi keterbatasan dokumen.
Artinya, hukum tidak pernah menutup pintu solusi.
Namun yang terjadi di Boyolali justru sebaliknya. Kesaksian warga sekitar diabaikan, bahkan keterangan Kepala Desa—sebagai pejabat pemerintahan yang paling mengetahui kondisi warganya—tidak dipertimbangkan secara layak. Pendekatan ini bukan hanya kaku, tetapi berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum administrasi negara.
Dalam konteks ini, tindakan pelayanan tanpa solusi patut diduga sebagai maladministrasi, sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik.
Negara tidak boleh bersembunyi di balik kalimat “aturan tidak memungkinkan”, ketika aturan justru menyediakan ruang diskresi dan penyelesaian alternatif. Diskresi pejabat diakui dalam sistem hukum administrasi sepanjang digunakan untuk kepentingan umum dan keadilan, bukan untuk menghindari tanggung jawab.
Ketika jalur pelayanan administratif menemui jalan buntu, warga pada akhirnya dipaksa menempuh jalur hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung menjadi tumpuan terakhir untuk memperoleh kepastian hak sipil—sebuah ironi, mengingat hak tersebut seharusnya dapat dipenuhi di meja pelayanan dasar.
Sebagai puncak peradilan, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi memutus sengketa, tetapi juga memberi arah bagi tata kelola pemerintahan agar tidak terjebak pada legalisme sempit. Putusan pengadilan kerap menegaskan bahwa administrasi negara harus melayani, bukan mempersulit.
Kasus Disdukcapil Boyolali ini menjadi peringatan serius bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik di Indonesia. Bila birokrasi kehilangan orientasi solusi, maka negara berisiko kehilangan kepercayaan warganya.
Pelayanan publik tidak boleh berhenti pada kata tidak bisa.
Ia harus berlanjut pada komitmen: bagaimana negara memastikan hak warga tetap terlindungi, meski di tengah keterbatasan dokumen.
Itulah ukuran negara yang beradab.(jhon)